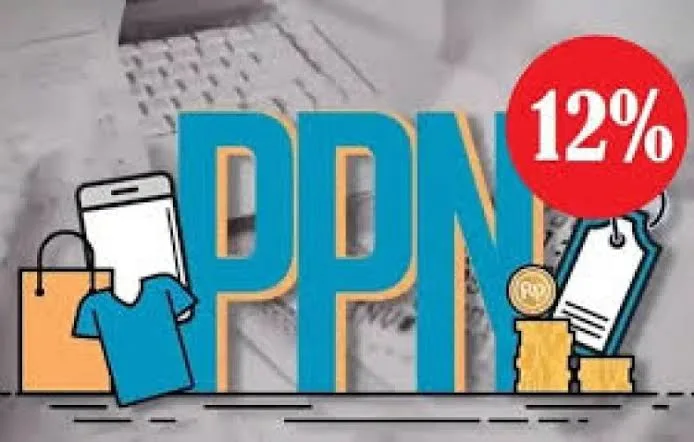OPINI,mediasulutgo.com — Awal tahun 2025 ini, masyarakat dibuat ketar-ketir oleh kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2025.
Pada konferensi pers yang diadakan di Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta Pusat pada Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan, “Untuk lebih jelasnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah, yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah dan dikonsumsi oleh golongan masyakat berada atau masyarakat mampu.”
Dalam konferensi pers yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan tentang barang-barang mewah apa saja yang akan terkena kenaikan tarif PPN sebesar 12%. Ia mengatakan, “Nah, itu kategorinya sangat sedikit, limited, yaitu barang seperti private jet, kapal pesiar, dan juga rumah yang sangat mewah dan nilainya itu sudah diatur di dalam PMK mengenai PPN barang mewah nomor 15 tahun 2023.” (ANTARA, 31/12/2024).
Pernyataan ini sedikit melegakan bagi masyarakat menengah ke bawah, setidaknya kebutuhan pokok sehari-hari meraka masih berada dalam harga normal karena kenaikan pajak tersebut diperuntukkan untuk barang-barang mewah yang hanya digunakan oleh orang-orang kaya. Namun sayangnya untuk memahami narasi dari pemerintah ini tidak semudah dan sesederhana itu.
Menurut Ajib Hamdani, seorang Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), pernyataan pemerintah bahwa tarif PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah tidaklah sepenuhnya benar. Menurutnya, untuk barang dengan nilai lain, acuan pembayaran PPN tetap 12% meskipun itu bukan barang mewah, seperti agen travel, perdagangan emas, dll. Pada akhirnya konsumenlah yang harus membayar harga akhir yang telah menjadi lebih tinggi.
Fakta ini menunjukkan bahwa kenaikan pajak tidak hanya berdampak pada pihak yang dikenakan pajak, tetapi juga akan berdampak langsung pada semua orang, termasuk rakyat kecil meski secara tidak langsung.
Meskipun kenaikan tarif PPN ini hanya diberlakukan untuk barang dan jasa premium, namun hal tersebut juga berdampak pada semua orang, termasuk pedagang, konsumen, dan para ahli ekonomi. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pengusaha yang terkena pajak akan menaikkan harga jual barang yang mereka produksi karena biaya produksi naik, dan karena harga barang dan jasa menjadi lebih mahal, konsumen akan merasa lebih sulit untuk membeli barang-barang tersebut. Di sisi lain, perusahaan ritel besar juga khawatir tentang penurunan penjualan yang mungkin terjadi.
Sampai hari ini pemerintah masih belum juga memberikan tanda-tanda untuk membatalkan kebijakan ini meskipun telah mendapatkan perlawanan dan kritik dari masyarakat, hingga mereka memunculkan petisi yang telah ditandatangani oleh ratusan ribu orang di media sosial. Pemerintah malahan memberikan sejumlah alasan untuk membenarkan keputusannya.
Dilansir dari CNBC Indionesia, Sri Mulyani mengungkapkan secara terang-terangan bahwa alasan mengapa masyarakat harus membayar pajak karena nantinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama pada tahun 2024, akan dialokasikan sebesar 20% untuk sektor pendidikan dalam negeri (4/1/2025).
Selain itu, pemerintah juga memberikan iming-iming adanya stimulus yang seolah menjadi uang tutup mulut agar masyarakat tidak merengek karena diterapkan kebijakan ini. Stimulus tersebut antara lain berupa bansos dengan diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kilogram selama dua bulan. Tak lupa pula memberikan insentif pajak, seperti perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5% untuk UMKM; Insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk industri padat karya; dan berbagai insentif PPN lainnya dengan total alokasi mencapai Rp265,6 T untuk tahun 2025.
Namun masalahnya adalah tujuan dari kenaikan tarif PPN sebesar 12% serta solusi untuk efek yang ditimbulkannya masih sebatas klaim semata. Sehingganya kita sudah dapat memprediksikan, lagi-lagi rakyatlah yang harus dikorbankan untuk menanggung pahitnya getah demi menyukseskan kepentingan negeri ini.
Ditambah lagi dengan kenaikan inflasi yang dipastikan akan meningkat dan memicu tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok miskin dan menengah. Pada kenyatannya tujuan indah dan mulia yang diharapkan pemerintah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, kini hanya membuat rakyat semakin tercekik.
Dari sini kita dapat melihat negara seolah berusaha untuk cuci tangan dengan menyebutkan berbagai program yang diklaim untuk mensejahterakan rakyat, namun sejatinya abai terhadap penderitaan rakyat. Seperti halnya narasi dari naiknya pajak 12% guna membantu membiayai proyek dan program pemerintah, yang untungnya juga akan dikembalikan dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Nyatanya narasi ini berbeda dengan fakta di lapangan.
Apabila dianalisis lebih lanjut, anggaran untuk menyukseskan program pemerintah seperti makan gizi gratis untuk anak-anak diambil dari hasil uang pajak rakyat. Ini sama saja dengan orang tua dari anak-anak tersebut juga yang memberikan makan anaknya sendiri tapi bedanya melalui piring yang disediakan oleh pemerintah. Lantas rakyat mana sebenarnya yang ingin di sejahterakan oleh pemerintah?
Biang Kesengsaraan
Biang kesengsaraan dari naiknya PPN hingga 12% ini tidak lain adalah buah dari penerapan sistem yang sebenarnya hanya menguntungkan para oligarki namun membawa-bawa kata “untuk rakyat” pada slogannya. Ialah demokrasi-kapitalisme, sistem megah yang telah berdiri kokoh selama bertahun-tahun dan terus dipelihara oleh para elit.
Pajak adalah salah satu instrumen dan sumber utama pendapatan negara dalam sistem kapitalisme yang membantu pemerintah mendanai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Selain itu, digunakan untuk mengurangi defisit anggaran yang mungkin terjadi karena belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan. Selain itu, kenaikan PPN juga tidak lepas dari standar internasional yang dibuat oleh manusia supaya tidak kalah saing dengan negara lain yang menetapkan PPN yang lebih besar dibandingkan negara Indonesia.
Dengan alasan-alasan yang telah diuraikan, kebijakan menaikkan pajak ini terus dilakukan tanpa mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sistem ini selalu mengedepankan kepentingan para pemilik modal besar daripada kepentingan masyarakat biasa. Dalam sistem kapitalisme, pertumbuhan ekonomi berpusat pada kapital, sementara posisi negara hanya sebagai regulator yang membantu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, konsumsi pajak seperti PPN terus didorong oleh negara kepada masyarakat kecil karena lebih mudah dipungut daripada memungut pajak dari perusahaan besar atau orang kaya.
Sementara untuk sektor strategi industri seperti energi, pertambangan, dan infrastruktur sering diprivatisasi. Akibatnya, pendapatan negara dari SDA menjadi berkurang. Karena SDA tidak lagi menjadi sumber pendapatan utama negara, pemerintah harus bergantung pada pajak, yang sering kali dengan cara menaikkan tarif pajak sebagai penggantinya. PPN cenderung memberikan beban pajak kepada kelompok menengah ke bawah dan miskin. Alhasil masyarakat biasa ini tidak dapat menolak dan hanya bisa mengikuti permainan yang disediakan karena mereka tidak memiliki orang dalam yang kuat sebagaimana para pemilik modal, yang membuat mereka berpeluang mendapatkan keringanan pajak atau bahkan “lolos” dari kewajiban pajak. Dengan demikian, kita dapat mengindra bahwa dalam sistem kepemimpinan sekuler demokrasi hari ini, ketika membuat kebijakan hanya semakin menguatkan profil penguasa yang populis otoriter, dimana keberpihakan seolah hanya condong pada segelintir rakyat saja, tepatnya pada rakyat yang punya uang untuk menyumpal para penguasa agar membuat kebijakan yang berat sebelah.